Satu hal yang jadi persoalan bagi guru SD seperti saya di akhir tahun pelajaran adalah tentang kenaikan kelas. Sederhana, tapi bisa jadi sesuatu yang rumit. Kadang, pengen nggak naikin kelas kalau ngeliat anak yang kewalahan ngikutin pelajaran di kelas, tapi kasian juga kalau anak itu harus ngulang lagi selama satu tahun, yang sebenernya juga belum tentu bisa banyak mengubah keadaan kalau setahun lagi di kelas yang sama.
Dulu, waktu masih ngajar di SD negeri. Naik atau enggaknya siswa, semuanya saya yang memutuskan. Positifnya, saya yang paling tahu keadaan anak di kelas, paling ngerti bagaimana kemampuan anak sehari-hari. Jadi, memang saya yang paling berhak memutuskan. Negatifnya, bisa bikin nyesel berkepanjangan kalau salah ambil keputusan. Ya...yang namanya orang dalam mengambil keputusan kadang juga butuh masukan dari orang lain.
Sekarang, saya memang bisa lebih tenang menghadapi persoalan ini karena di sekolah saya yang sekarang, penentuan kenaikan kelas nggak cuma jadi tanggung jawab wali kelas seorang diri tapi kepala sekolah dan juga wali kelas lainnya.
Jadi, setiap selesai ujian kenaikan kelas, para wali kelas dan guru mata pelajaran dikumpulin jadi satu dan diminta laporan siapa saja anak-anak yang sepertinya punya jalan terjal untuk naik ke kelas selanjutnya. Lalu didiskusikan bareng-bareng, ditunjukkan aspek lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat tetap bisa naik kelas.
Membuat anak mengulang satu tahun di kelas yang sama bukan hal yang mudah bagi wali kelas. Bisa saja, saya bakalan diingat sampai kapan pun sebagai wali kelas jahat yang pernah membuat anak tadi nggak naik kelas. Bisa juga, karena ternyata ada hal lain yang terlambat saya sadari setelah membuat keputusan anak nggak naik kelas, saya jadi menyesal berkepanjangan.
Dan saya pernah melakukan itu...
Dulu, di tempat pertama saya ngajar, SDN 04 Penggarit yang sekarang sudah tinggal kenangan karena sekolahnya terpaksa dimerger atau digabung dengan sekolah sebelah karena sekolah saya kekurangan siswa.
Saya pernah dua kali jadi wali kelas di sekolah itu, selama dua tahun saya ngajar kelas tiga SD. Selama itu juga setiap tahunnya pasti ada anak yang nggak saya naikkan kelas. Selama ini saya berpikir itu wajar karena mereka memang belum bisa menguasai materi dan sulit mengikuti pelajaran yang ada selama ini.
Debut pertama saya sebagai wali kelas berujung dua anak tidak saya naikkan kelas. Yang pertama, sebut saja Annur. Dia belum bisa baca sampai kelas tiga, sebelumnya sudah dua kali nggak naik kelas masing-masing satu kali di kelas satu dan kelas dua.
Sampai di kelas tiga pun, Annur masih belum lancar membaca. Jadi, setiap ada ulangan harian, UTS sampai ulangan akhir semester. Annur selalu menjawab sembarangan di setiap lembar jawabnya. Sudah begitu, meskipun Annur punya postur yang tinggi dan besar dibanding anak kelas tiga lainnya, tapi Annur masih sering nangis dinakalin sama teman sekelasnya. Annur adalah korban bully-an teman-temennya, walaupun saya juga sudah sering menegur anak-anak yang membully-nya.
Waktu itu, saya pun akhirnya memutuskan Annur untuk tidak naik kelas, berharap Annur ada banyak perubahan di tahun kedua sebagai siswa kelas tiga. Sayangnya, di tahun kedua bareng saya sebagai anak kelas tiga (lagi). Annur masih belum ada banyak perubahan. Nulis masih suka ngasal, yang akhirnya jadi nggak bisa dibaca. Annur masih kesulitan buat bisa membaur sama teman-temennya. Annur juga masih suka nangis tiap dinakalin temennya.
Walaupun setiap Annur nangis, saya selalu manggil anak yang nakalin buat minta maaf dan ngasih tahu biar nggak nakalin lagi. Tapi, yang namanya anak-anak, besoknya tetap aja diulangin lagi.
Suatu waktu, pernah beberapa kali Annur nggak ngerjain PR. Saya sempat mengancam kalau seperti itu terus, saya bakal panggil orangtuanya ke sekolah. Besoknya, orangtua Annur beneran datang ke sekolah dengan raut wajah yang cemas. Khawatir anaknya berbuat kesalahan yang fatal sampai ibunya harus menghadap wali kelasnya.
Saya juga sempat kaget karena sebenarnya saya nggak beneran manggil orangtuanya Annur. Tapi ternyata, Annur mengira saya beneran mau ketemu sama orangtuanya. Jadi, kami berdua sama-sama kaget siang itu. Berhubung saya ngajar di sekolah daerah pedesaan, orangtua siswa disini rata-rata beneran menghormati gurunya. Jadi orangtua Annur bersikap sangat sopan sama saya, saya jadi ngerasa nggak enak banget.
Karena sudah terlanjur ketemu, akhirnya saya pun ngobrol sama ibu Annur di ruang tamu. Hari itu, saya baru tahu kalau ternyata tiap malem Annur terus berusaha belajar untuk bisa membaca. Annur terus latihan berhitung matematika, biar bisa mengejar ketinggalannya. Annur juga sempat bilang ke ibunya, kalau dia nanti lulus SD dia minta nggak usah lanjut sekolah ke SMP. Saya ngerasa meleleh waktu ibunya niruin apa yang diucapin Annur. “Mak, Annur sekolahnya sampai lulus SD aja, ya. Nanti Annur nggak usah lanjut SMP. Annur capek, pelajarannya susah-susah. Annur di rumah aja, ya.. nanti Annur bantuin Emak wes tiap hari.”
Ibunya yang sangat paham kondisinya Annur mengiyakan itu, dan untuk saat ini memotivasi Annur agar bisa nyelesein SD dulu, sekalipun harus nggak naik kelas terus.
Hari itu saya beneran ketampar banget.
Selama ini Annur memang orangnya pendiam banget. Saya pun sering kesulitan kalau ngajak ngobrol karena seringnya pertanyaan saya hanya dijawab dengan anggukan dan gelengan saja. Akhirnya, hari itu saya tahu, kalau Annur sebenarnya udah berjuang keras di rumah. Saat saya nulis ini, harusnya tahun ini Annur masuk SMP kalau memang Annur naik terus.
Mendadak saya jadi ingin tahu bagaimana keadaan Annur. Penasaran, apakah dia masih berjuang untuk sekolah di SMP, atau justru sudah nyerah. Rasanya saya juga pengen ketemu, duduk bareng... mungkin untuk minta maaf karena saya waktu itu nggak bisa jadi ‘teman’ yang bener-bener ngerti keadaan Annur. Saya udah gagal memahami Annur, anak yang spesial yang dipertemukan dengan saya.
Saya baru sadar, dulu saat saya memutuskan untuk nggak naikin Annur ke kelas empat. Pikiran saya hanya sesederhana Annur nggak bakalan bisa ngikutin pelajaran di kelas empat. Annur bakalan kepayahan di kelas empat.
Saya nggak mikir panjang, bahwa Annur setahun lagi di kelas tiga pun nggak akan menjamin setahun berikutnya Annur bakalan bisa lebih siap menghadapi kerasnya kelas empat. Saya juga harusnya tahu, Annur punya orangtua di rumah yang juga berjuang bareng dan nggak membiarkan anaknya sendirian menghadapi pelajaran di kelas empat nanti dan Annur mungkin puya potensi lain selain di bidang akademik.
Sampai sekarang saya masih merasa bersalah sama keputusan saya waktu itu. Karena sebenarnya naik kelas atau enggak, Annur akan tetap menghadapi jalan terjal, jalan yang lebih berat dibanding temannya di kelas empat. Lalu, saya bukannya memberikan support untuk Annur, saya justru memberikan penghalang besar yang membuatnya harus berhenti melewati jalan terjal itu selama setahun.
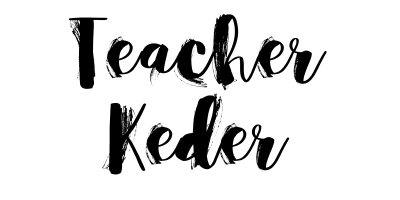







.jpg)






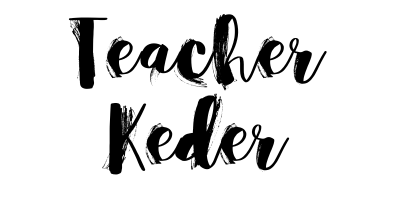
2 Komentar
Wah padahal masih sekecil itu ya. Setiap orang emang udah punya perjuangannya masing-masing ya. *jadi mikir soal keputusan yang udah dibuat sendiri*
BalasHapussedih amat ya anak bernama Annur ini, bikin gua memelas karena keluguannya gak mau sekolah lagi dan lebih milih bantu orang tuanya. Gua juga guru SMP, dan kayaknya sifat murid2 gua gak jauh beda dengan murid lu Dot, kadang ada yg suka ngbully, dsb. Dan begitu pula sakitnya penyesalan gua, waktu gua pengen ngeluarin anak yang nakalnya naudzubillah, dan ironisnya si orang tua anak ini sopan banget sampe segen dan malu gua pengen ngelakuin hal itu
BalasHapus